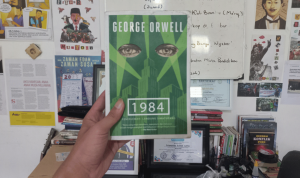Oleh : Alfin Maulana, Korwil Karesidenan Tapal Kuda BEM Nusantara Jawa Timur
Pernyataan Prabowo Subianto mengenai kemungkinan pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh DPRD memunculkan diskursus serius dalam lanskap demokrasi Indonesia.
Wacana ini segera memantik perdebatan publik, terutama karena sering dibingkai sebagai solusi atas persoalan mahalnya biaya pilkada langsung dan tingginya potensi konflik horizontal.
Namun, kritik terhadap gagasan ini kerap disalahpahami seolah-olah menolak efisiensi anggaran negara. Padahal, titik kritis utama dari penolakan tersebut tidak terletak pada tujuan efisiensinya, melainkan pada perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah itu sendiri yang berimplikasi langsung terhadap kedaulatan rakyat dan kualitas demokrasi lokal.
Dalam demokrasi, tidak semua tujuan baik dapat membenarkan cara yang ditempuh. Efisiensi anggaran, stabilitas politik, dan pengurangan konflik memang merupakan tujuan yang secara normatif dapat diterima dalam tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Opini: Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah
Akan tetapi, demokrasi tidak dapat direduksi menjadi persoalan teknokratis tentang penghematan biaya. Demokrasi adalah sistem normatif yang menjamin hak politik warga negara untuk berpartisipasi secara setara dalam menentukan arah kekuasaan.
Ketika mekanisme pemilihan kepala daerah dipindahkan dari rakyat ke DPRD, yang dipertaruhkan bukan sekadar efisiensi, melainkan hak fundamental rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Dalam teori demokrasi, pemilihan langsung merupakan instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat. Robert A. Dahl menegaskan bahwa partisipasi politik yang luas dan setara merupakan prasyarat minimum demokrasi modern.
Melalui pemilihan langsung, relasi mandat antara pemilih dan pemimpin menjadi jelas: kepala daerah memperoleh legitimasi langsung dari rakyat dan karenanya bertanggung jawab kepada mereka.
Baca Juga: Opini: Semangat Pemuda untuk Indonesia Emas
Sebaliknya, pemilihan oleh DPRD menggeser relasi tersebut menjadi tidak langsung dan elitis. Mandat politik kepala daerah tidak lagi bersumber terutama dari warga, melainkan dari konfigurasi kepentingan partai dan fraksi legislatif.
Kritik terhadap mekanisme pemilihan oleh DPRD semakin relevan jika ditinjau dari pengalaman empiris Indonesia sebelum pilkada langsung diberlakukan. Sejumlah studi tentang politik lokal menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pada masa lalu sarat dengan praktik transaksi politik tertutup.
Penelitian Fitrani, Hofman, dan Kaiser (2005) menunjukkan bahwa desentralisasi tanpa partisipasi langsung rakyat justru memperkuat oligarki lokal dan memperluas ruang negosiasi elite.
Dalam konteks tersebut, pemilihan oleh DPRD bukanlah mekanisme yang netral, melainkan sangat rentan terhadap kooptasi kepentingan sempit dan politik balas jasa.
Baca Juga: Membaca Ulang Predikat SAKIP Kota Blitar: Antara Citra dan Realita
Dalam kerangka ini, efisiensi anggaran menjadi argumen yang bersifat sekunder. Bahkan jika benar bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat mengurangi biaya pemilu, penghematan tersebut tidak otomatis berarti peningkatan kualitas demokrasi.
Larry Diamond menegaskan bahwa demokrasi selalu memiliki cost, dan biaya tersebut merupakan investasi untuk menjaga legitimasi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik.
Menghapus pemilihan langsung demi efisiensi justru berisiko menciptakan biaya politik lain yang lebih mahal, seperti menurunnya legitimasi pemerintahan daerah dan meningkatnya apatisme serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik.
Lebih jauh, pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi melemahkan akuntabilitas vertikal. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki insentif politik untuk merespons kebutuhan publik karena kelangsungan kekuasaannya bergantung pada dukungan pemilih.
Baca Juga: GPI Tegaskan Komitmen Kawal Pemerintahan Prabowo hingga Daerah, Fokus Awasi Korupsi dan Pendidikan
Sebaliknya, ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, orientasi kebijakannya cenderung diarahkan untuk menjaga hubungan dengan elite legislatif dan partai politik. Kondisi ini mempersempit ruang kontrol publik dan mengaburkan mekanisme pertanggungjawaban demokratis yang seharusnya berjalan dari bawah ke atas.
Argumen bahwa pemilihan oleh DPRD dapat mengurangi konflik juga perlu dikritisi secara serius. Konflik dalam pilkada langsung tidak dapat disederhanakan sebagai akibat dari mekanisme pemilihan semata.
Banyak riset menunjukkan bahwa konflik lebih sering dipicu oleh lemahnya penegakan hukum, politisasi identitas, dan rendahnya literasi politik masyarakat.
Mengganti mekanisme pemilihan tanpa membenahi faktor-faktor struktural tersebut justru berisiko memindahkan konflik dari ruang publik yang relatif transparan ke ruang tertutup elite politik.
Dari sudut pandang keadilan demokratis, perubahan mekanisme ini juga bermasalah. Demokrasi beroperasi atas asas kesetaraan politik (political equality), di mana setiap warga memiliki hak yang sama dalam menentukan pemimpin. Ketika hak tersebut didelegasikan sepenuhnya kepada DPRD, terjadi pengurangan derajat partisipasi rakyat.
Baca Juga: Banjir di Kabupaten Jember: Antara Bencana Alam dan Krisis Tata Kelola Lingkungan
Dalam kerangka keadilan John Rawls, pengurangan hak dasar politik tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan manfaat administratif atau efisiensi. Hak politik bukanlah privilese yang dapat dinegosiasikan, melainkan hak dasar yang melekat pada warga negara.
Pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi lokal. Persoalan utama bukan terletak pada soal efisiensi anggaran, melainkan pada hilangnya hak politik rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Apabila negara mulai menukar kedaulatan rakyat dengan logika efisiensi, maka demokrasi berisiko direduksi menjadi sekadar prosedur administratif yang miskin legitimasi. (Ha/serayu)